Pengamat Ungkap Dasco 'Royal' Bayar Takedown Berita demi Jaga Privasi Keluarga

Wakil Ketua DPR-RI dari Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad (Bung Dasco),

Radarriaunet || Jakarta – Praktik penghapusan tautan (link) berita atau takedown di media daring kini berkembang menjadi paradoks tersendiri dalam industri pers nasional. Di satu sisi, Dewan Pers memegang teguh mekanisme koreksi melalui jalur resmi, namun di sisi lain, pragmatisme ekonomi membuat jalur transaksional menjadi pilihan yang menggoda bagi sebagian pengelola media.
Benteng Regulasi Dewan Pers
Dalam sebuah acara di Jakarta, Selasa (2/12/2025), Ketua Dewan Pers, Prof. Komaruddin Hidayat, kembali menegaskan marwah jurnalisme yang tidak boleh diintervensi oleh pihak luar secara sepihak. Ia menekankan bahwa sengketa pemberitaan memiliki kanal penyelesaian yang bermartabat.
“Selama teman-teman menjalankan kerja jurnalistik yang benar, taat aturan, objektif, dan profesional, itu sudah cukup,” ujar Komaruddin.
Dewan Pers menggarisbawahi bahwa permintaan takedown berita tidak bisa dilakukan by request atau sekadar karena ketidaksukaan narasumber. Prosedurnya jelas: pengaduan, analisis, mediasi, hak jawab, dan koreksi. Takedown adalah opsi terakhir (ultimum remedium) jika dan hanya jika ditemukan pelanggaran kode etik berat.
Jalur Pintas Transaksional
Namun, realitas di lapangan kerap tidak sejalan dengan regulasi di atas kertas. Pengamat Media dari Litbang Demokrasi, Purbo Satrio, mengungkap sisi lain dari ekosistem media non-mainstream. Menurutnya, ada "wilayah abu-abu" di mana penghapusan berita menjadi komoditas bisnis.
Bagi tokoh publik, terutama politisi, prosedur Dewan Pers dianggap terlalu birokratis dan memakan waktu. Saat sebuah isu sensitif mencuat, kecepatan untuk meredam isu adalah kunci, dan uang menjadi alat pelicin yang efektif.
“Takedown sepihak sering dilakukan oleh tokoh politik yang tidak ingin memperlebar sebuah isu. Dia memilih jalur transaksional dengan sejumlah uang sebagai pengganti berita yang dihapus, daripada harus melalui prosedur mekanisme Dewan Pers,” ungkap Purbo.
Sorotan pada Dasco: Privasi Berbayar?
Purbo secara spesifik menyoroti nama Wakil Ketua DPR-RI dari Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad (Bung Dasco), sebagai figur yang cukup dikenal di kalangan jurnalis media non-mainstream dalam praktik ini.
Menurut pengamatan Purbo, Dasco memiliki tim lapangan yang solid dan bergerak taktis untuk melobi pemilik media. Uniknya, alasan takedown yang diminta tim Dasco tidak melulu soal sentimen negatif politik. Belakangan, tren menunjukkan adanya upaya perlindungan privasi keluarga yang dilakukan melalui jalur berbayar ini.
“Bung Dasco salah satu tokoh yang royal membelanjakan dananya untuk kepentingan takedown berita... Tidak hanya berita negatif, belakangan ini marak pemberitaan terkait istri dan anaknya diminta takedown,” jelas Purbo.
Fenomena ini menarik karena berita yang diminta hapus terkadang bernada positif. Namun, karena keengganan sang tokoh agar keluarganya terekspos (privasi), opsi takedown berbayar tetap diambil. Ini menunjukkan bahwa bagi figur sekelas Dasco, kendali atas narasi publik—baik positif maupun negatif—adalah prioritas yang layak dibiayai.
Simbiosis Mutualisme?
Bagi sebagian pemilik media daring lapis kedua atau non-mainstream, tawaran ini sulit ditolak. Di tengah seretnya kue iklan konvensional, dana kompensasi takedown menjadi pos pemasukan segar (revenue stream) di luar kerja sama rilis.
Dalam kacamata ini, praktik tersebut tidak lagi dilihat sebagai "pembungkaman pers", melainkan negosiasi bisnis semata untuk meredam isu yang sedang hangat. Karena keputusan akhir berada di tangan pemilik media tanpa paksaan fisik, praktik ini terus langgeng meski bertentangan dengan semangat independensi pers yang digaungkan Dewan Pers.
(Red)
-

Program Irigasi P3A-TGAI di Melawi Dorong Pemberdayaan Petani dan Ekonomi Desa
-

Polisi Buru Peretas Situs Polda Riau
-

Koalisi Gemuk Pengawasan Melemah
-

Polisi Tetapkan 34 Tersangka Kerusuhan Mimika, 13 Diduga KNPB
-

Pengadilan Tunda Sidang Kasus Foto Jokowi dan Nikita Mirzani
-

AS Resmi Buka Kedubes untuk Israel di Yerusalem
-
1View
33098Laporan Kekayaan Menonjol Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad
-
2View
662Pengamat Ungkap Dasco 'Royal' Bayar Takedown Berita demi Jaga Privasi Keluarga
-
3View
1756Bupati Rohil: Bistamam Digugat ke PTUN, Kadisdik Pekanbaru Terseret Kasus SKPI Cacat Formil
-
4View
1836Skandal Ijazah Palsu Melilit Bupati Rohil: Bistamam Dilaporkan ke Mabes Polri, Ijazah SMEA Tahun 1968 Diduga Fiktif
-
5View
3407Jasaraharja Putera Salurkan Bantuan Darurat untuk Mahasiswa Terdampak Banjir di Kota Padang
-
6View
4563Eksepsi Nurhadi: Tuduhan Mengambang, Standar Ganda, dan Pertaruhan Keadilan di Pengadilan Tipikor
-
7View
5386Jasaraharja Putera Gelar Donor Darah Dalam Rangka Road To HUT Ke-32: Wujud Kepedulian untuk Sesama
-
8View
6051MVG Bangun Komunitas Event Terkuat di Indonesia, Pertegas Posisi di JAVME 2025
-
9View
8157Jelang Puncak Mobilitas Nataru, Terminal Kalideres Mulai Lakukan Pengawasan Ketat Armada Bus AKAP
-
10View
8693Jasaraharja Putera Gelar Kegiatan CSR di Kampung Pemulung Lapak Sarmili Bambu Pelangi dalam Road to HUT ke-32
-
1View
33098Laporan Kekayaan Menonjol Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad
-
2View
662Pengamat Ungkap Dasco 'Royal' Bayar Takedown Berita demi Jaga Privasi Keluarga
-
3View
1756Bupati Rohil: Bistamam Digugat ke PTUN, Kadisdik Pekanbaru Terseret Kasus SKPI Cacat Formil
-
4View
1836Skandal Ijazah Palsu Melilit Bupati Rohil: Bistamam Dilaporkan ke Mabes Polri, Ijazah SMEA Tahun 1968 Diduga Fiktif
-
5View
3407Jasaraharja Putera Salurkan Bantuan Darurat untuk Mahasiswa Terdampak Banjir di Kota Padang
-
6View
4563Eksepsi Nurhadi: Tuduhan Mengambang, Standar Ganda, dan Pertaruhan Keadilan di Pengadilan Tipikor
-
7View
5386Jasaraharja Putera Gelar Donor Darah Dalam Rangka Road To HUT Ke-32: Wujud Kepedulian untuk Sesama
-
8View
6051MVG Bangun Komunitas Event Terkuat di Indonesia, Pertegas Posisi di JAVME 2025
-
9View
8157Jelang Puncak Mobilitas Nataru, Terminal Kalideres Mulai Lakukan Pengawasan Ketat Armada Bus AKAP
-
10View
8693Jasaraharja Putera Gelar Kegiatan CSR di Kampung Pemulung Lapak Sarmili Bambu Pelangi dalam Road to HUT ke-32
-

Ultimatum Langsung dari Istana: Presiden Prabowo Jamin Perlindungan bagi Pelapor dan Tuntut Hati Nurani Polri-Kejaksaan
-
Satu Tahun Kabinet Merah Putih: Ujian Integritas, Keadilan Ekonomi, dan Jangkauan Program
-
Nasi Goreng Favorit Kepala Negara, Simbol Keseragaman Gizi di Hari Ulang Tahun Presiden Prabowo
-

Pemkab Bengkalis Komitmen Penuh dalam Studi Kelayakan Jembatan Dumai–Melaka: Dorong Konektivitas Regional dan Kesejahteraan Ekonomi
-
DPRD Riau Ungkap Keputusan Pemangkasan TKD 2026 Belum Final, Kemenkeu Prioritaskan Bukti Kinerja Daerah
-
Aksi Protes di Pekanbaru: Ratusan Warga Tuntut Keadilan atas Dugaan Penyerobotan Lahan oleh Mafia Tanah











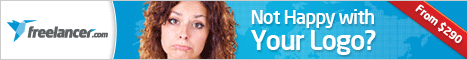





.jpeg?w=200)



