Transaksi dalam Ruang Gelap MA
Administrator - Rabu, 17 Februari 2016 - 22:19:02 wib

Laode Ida. (mtnc)

Penulis: Laode Ida, Wakil Ketua DPD RI 2004-2014, Komisioner Ombudsman RI
RADAR RIAU NET OPINI - KASUS tertangkapnya seorang pejabat di Mahkamah Agung (MA), Agung Andri Tristianto (AAT) berikut seorang pengusaha (Ichsan Suaidi) dan kuasa hukum (Awang Lazuardi Embat), melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dengan korupsi proyek pembangunan dermaga Labuhan Haji di Lombok Timur (NTB), kembali mencoreng citra dari benteng penjaga keadilan yang tertinggi itu.
Peristiwa itu membuktikan putusan hukum yang sudah berketetapan dengan substansi memperkuat hukuman bagi para koruptor pun ternyata bisa dimainkan pejabat yang menangani administrasinya.
Motifnya jelas untuk 'mengaburkan' atau 'memperlambat eksekusi putusan hakim', seraya memperoleh uang dari pihak terdakwa.
Menariknya lagi, kasus putusan yang hendak ditransaksikan itu ialah produk Artidjo Alkostar yang terkenal sebagai algojo untuk para koruptor yang mencoba memperoleh keringanan (atau pembebasan dari) hukuman melalui proses kasasi di MA.
Ini bisa diartikan bahwa putusan beradilan dan sarat integritas tidak didukung sepenuhnya sebagian pihak administrator elemen sistem pendukung di intern lembaga peradilan tertinggi itu sekaligus menunjukkan ketidaksenangan mereka terhadap figur hakim agung yang 'ganas' terhadap para koruptor.
Praktik transaksional yang dilakukan AAT itu bukan mustahil sudah jadi bagian dari karakter (sebagian) aparatur negara di MA.
Ia tentu tidak sendirian karena bekerja dalam suatu sistem dengan perilaku yang boleh jadi sudah saling 'tahu sama tahu' alias TST.
Tidak mengherankan kalau tidak sedikit di antara pejabatnya yang miliki kekayaan materi jauh melebihi rasio gaji normal baik sebagai PNS maupun hakim agungnya.
Kita semua tahu bahwa yang ditangani MA bukan saja kasasi kasus korupsi, melainkan juga berbagai kasus strategis nan 'basah' lainnya, seperti sengketa tanah (lahan), narkoba, dan lainnya; semuanya bisa diperjualbelikan seperti yang dilakukan AAT.
Tidak mengherankan kalau tak sedikit kasus sengketa tanah bukan saja mengendap lama di MA, melainkan juga posisi rakyat biasa nan miskin umumnya kalah jika berhadapan dengan para pemilik modal atau orang-orang kaya.
Tepatnya, tak jarang rasa keadilan dipertukarkan dengan materi sehingga rakyat kecillah yang jadi korbannya dan pada saat yang sama, orang yang kaya semakin kaya dan aparatur di MA pun mengakumulasi harta.
Kita masih ingat, misalnya Sekretaris MA, Nurhadi yang miliki meja kerja senilai kurang lebih Rp1 miliar (terungkap pada November 2012), di mana juga yang bersangkutan menyelenggarakan pesta perkawinan anaknya sangat mewah di hotel berbintang lima (Hotel Mulia) seraya membagi-bagi Ipod pada sejumlah tamu undangan (Maret 2014).
Tampilan mewah dengan nuansa gaya hidup hedonis itu sungguh-sungguh tak masuk akal untuk bisa dilakukan jika tidak mengakumulasi harta dengan cara-cara koruptif atau dengan memanfaatkan jabatan dan peluang dalam proses-proses hukum yang bersifat final di MA seperti yang dilakukan AAT.
Dalam kaitan ini, bukan mustahil pula perilaku transaksional itu secara diam-diam sudah 'seizin' pimpinan atau sepengetahuan teman sejawatnya.
Hanya kebetulan saja kali ini AAT-lah yang 'pasang badan' dan kemudian nahas karena terkena OTT dari KPK.
Kondisi lembaga penentu atau penjaga keadilan terakhir dan final seperti itu sungguh sangat memprihatinkan.
Sebuah potret kegagalan dalam membangun pulau integritas dan transparansi di dalamnya.
Mengapa?
Pertama, posisi jabatan strategis ternyata masih diisi figur-figur yang pragmatis dan transaksional.
Ini boleh jadi merupakan warisan masa lalu yang sudah mendarah daging di MA, yakni mereka sudah menerapkan prinsip keadilan harus ditukar dengan materi dan tak ada keadilan bagi yang tak miliki nilai tukar. Semakin banyak yang beperkara di MA, akan semakin banyak juga pemasukan di luar gaji dan berbagai tunjangan.
Tepatnya, dalam bahasa Presiden Jokowi, bisa dikatakan bahwa MA gagal melakukan revolusi mental.
Praktik korupsi atau transaksional di kalangan aparatur memang merupakan bagian dari kegagalan pimpinan dalam melakukan pengawasan internal terhadap aparatur bawahannya.
Soalnya, mengacu pada UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pimpinan suatu instansi secara langsung berperan mengawasi para aparatur bawahannya, selain pengawas internal fungsional yang jadi bagian dari dalam struktur kelembagaan (Pasal 35 ayat 2).
Tentu saja pengawasan dimaksud bukan sekadar formalitas belaka, melainkan lebih substansial terkait dengan penempatan aparatur yang bersih dan perilaku transaksional yang harus dicegah.
Yang terjadi sekarang, jika jujur diakui, umumnya instansi pemerintah, justru pihak atasan cenderung menempatkan aparat yang disenangi dan dipercayai untuk sekaligus dijadikan oknum pencari tambahan pendapatan melalui berbagai proyek ataupun transaksi kasus seperti AAT.
Kedua, jika jujur diakui, proses-proses penyelesaian kasus di MA selama ini masih sangat tertutup dan bahkan sulit diprediksi kapan bisa selesai atau sampai di mana perkembangan perkaranya sehingga sampai bertahun-tahun belum juga jelas nasibnya.
Saat jadi anggota/pimpinan DPD RI, penulis banyak menerima keluhan sekaligus permintaan untuk dicarikan jalan agar bisa dapat akses ke dalam MA.
Sungguh sangat menyedihkan jika perkara seperti itu dialami rakyat dari berbagai daerah di Indonesia, yakni mereka harus berurusan langsung di Jakarta dengan tanpa kepastian.
Pada akhirnya, pasrah menerima apa pun hasil putusan MA yang final itu.
Itulah bagian dari ruang gelap dalam proses-proses penyelesaian perkara di MA, yakni figur Artidjo Alkostar barangkali hanya berjuang dalam kesendirian tanpa topangan kuat dari pimpinan maupun administrator di intern lembaganya.
Berita Terkait
-

Polisi Imbau Jakmania Tak Bawa Senjata Tajam dan Mercon
-

Ahok Berbagi Kisah dari Penjara ke Warga Meruya
-

Kesaksian Istri Awak Mobil Tangki Penerobos Mobil Jokowi
-

Kapolri : Kasus SP3 Karhutla Riau Tak Boleh Dilakukan Langsung Oleh Polda Riau
-

Pengacara Irman Gusman Disebut Ingin Ajukan Praperadilan
-

JK Sebut Jabatan PNS Eselon III dan IV Akan Hilang
-
1View
13582Laporan Kekayaan Menonjol Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad
-
2View
1938Mengurai Benang Kusut Ledakan SMAN 72 — Antara Aksi Personal dan Bayang-bayang Radikalisme ?
-
3View
2516BGN Tutup Pintu Mitra MBG, Dugaan Pungli dan Penyimpangan Anggaran Menguat
-
4View
4368Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjaring OTT KPK
-
5View
4543Jasaraharja Putera Wujudkan Komitmen ESG Melalui Program Recycle Old Uniform dalam Road to HUT ke-32 Bertema Satunaya
-
6View
5837Ancaman Mutasi dan Kenaikan Fee 100 Persen: KPK Bongkar Pola Extortion Terstruktur Gubernur Riau Abdul Wahid di Proyek Jalan
-
7View
5725Reformasi Total Tata Kelola Musik: Menkumham Wajibkan Kodifikasi Karya demi Keadilan Royalti
-
8View
6271Jasaraharja Putera Raih Penghargaan TOP Human Capital Awards 2025, Komitmen Pengelolaan SDM Unggul dan Berkelanjutan
-
9View
6905Menko Yusril Bedah Dampak Ketimpangan Sosial-Ekonomi Terhadap 'Hukum Tumpul ke Atas
-
10View
8688Kawulo Alit Mendesak Presiden Prabowo: Bersihkan Mafia Pajak dan Bea Cukai! Pengakuan Mengejutkan Menkeu Jadi Pemicu
-
1View
13582Laporan Kekayaan Menonjol Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad
-
2View
1938Mengurai Benang Kusut Ledakan SMAN 72 — Antara Aksi Personal dan Bayang-bayang Radikalisme ?
-
3View
2516BGN Tutup Pintu Mitra MBG, Dugaan Pungli dan Penyimpangan Anggaran Menguat
-
4View
4368Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjaring OTT KPK
-
5View
4543Jasaraharja Putera Wujudkan Komitmen ESG Melalui Program Recycle Old Uniform dalam Road to HUT ke-32 Bertema Satunaya
-
6View
5837Ancaman Mutasi dan Kenaikan Fee 100 Persen: KPK Bongkar Pola Extortion Terstruktur Gubernur Riau Abdul Wahid di Proyek Jalan
-
7View
5725Reformasi Total Tata Kelola Musik: Menkumham Wajibkan Kodifikasi Karya demi Keadilan Royalti
-
8View
6271Jasaraharja Putera Raih Penghargaan TOP Human Capital Awards 2025, Komitmen Pengelolaan SDM Unggul dan Berkelanjutan
-
9View
6905Menko Yusril Bedah Dampak Ketimpangan Sosial-Ekonomi Terhadap 'Hukum Tumpul ke Atas
-
10View
8688Kawulo Alit Mendesak Presiden Prabowo: Bersihkan Mafia Pajak dan Bea Cukai! Pengakuan Mengejutkan Menkeu Jadi Pemicu
-

Ultimatum Langsung dari Istana: Presiden Prabowo Jamin Perlindungan bagi Pelapor dan Tuntut Hati Nurani Polri-Kejaksaan
-
Satu Tahun Kabinet Merah Putih: Ujian Integritas, Keadilan Ekonomi, dan Jangkauan Program
-
Nasi Goreng Favorit Kepala Negara, Simbol Keseragaman Gizi di Hari Ulang Tahun Presiden Prabowo
-

Pemkab Bengkalis Komitmen Penuh dalam Studi Kelayakan Jembatan Dumai–Melaka: Dorong Konektivitas Regional dan Kesejahteraan Ekonomi
-
DPRD Riau Ungkap Keputusan Pemangkasan TKD 2026 Belum Final, Kemenkeu Prioritaskan Bukti Kinerja Daerah
-
Aksi Protes di Pekanbaru: Ratusan Warga Tuntut Keadilan atas Dugaan Penyerobotan Lahan oleh Mafia Tanah
-

Jasaraharja Putera Wujudkan Komitmen ESG Melalui Program Recycle Old Uniform dalam Road to HUT ke-32 Bertema Satunaya
-
Babak Baru Reformasi Fiskal: Mendagri dan Menkeu Kompak Dorong Daerah Mandiri dan Efisien
-
JEBAKAN OBLIGASI? Pengamat Khawatir Danantara Terjebak Investasi Jangka Pendek, Pembangunan Jangka Panjang Terancam Stagnan
SITE INDEX











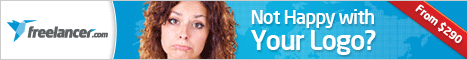




.jpeg?w=200)



